Penulis : Emi Adistiani
 |
| Sumber gambar: Gemini AI |
Gen Z sekarang punya cara pandang sendiri soal pekerjaan. Bagi mereka, pekerjaan itu penting, tapi bukan segalanya. Hidup juga butuh waktu buat istirahat, bertemu keluarga, dan mengurus diri sendiri. Namun, realitas di lapangan sering kali tidak seideal itu. Banyak perusahaan masih terjebak dalam budaya lama yang dimana menuntut karyawan selalu siap kapan pun, mengejar target tanpa henti, dan memuja lembur sebagai simbol loyalitas.. Lama-lama, tekanan seperti itu bikin capek bukan cuma fisik, tapi juga mental. Banyak anak muda akhirnya milih resign, bukan karena malas, tapi karena sudah tidak sanggup terus hidup dalam tekanan. Saya pernah dengar cerita dari seorang teman yang akhirnya mutusin buat resign. Dia bilang, “Aku udah coba sabar, tapi tiap hari rasanya kayak nggak pernah cukup. Sekecil apa pun yang aku lakuin, selalu salah di mata bos. Lama-lama aku ngerasa kerja bukan buat berkembang, tapi buat bertahan.” Cerita kayak gini bukan cuma satu dua. Banyak anak muda akhirnya sadar kalau kerja keras tidak ada artinya kalau setiap hari harus berhadapan sama tekanan yang bikin mereka kehilangan kepercayaan diri.
 |
| Sumber Gambar : Pribadi |
Fenomena resign ini menjadi alarm bagi banyak perusahaan. Gelombang resign dari pekerja muda bukan sekadar tren sesaat, tapi sinyal bahwa ada yang perlu diubah dalam cara dunia kerja beroperasi. Perusahaan dituntut beradaptasi, tidak hanya demi efisiensi, tapi juga demi kemanusiaan. Tempat kerja yang sehat, fleksibel, dan empatik bukan lagi bonus, melainkan kebutuhan. Kebijakan seperti jam kerja yang manusiawi, dukungan kesehatan mental, dan ruang untuk beristirahat akan meningkatkan loyalitas dan semangat karyawan. Ketika seseorang merasa dihargai, produktivitas akan tumbuh dengan sendirinya.
Perubahan juga perlu dimulai dari gaya kepemimpinan. Di masa kini, menjadi pemimpin bukan hanya mengatur, tetapi tentang memahami. Gen Z menghargai pemimpin yang mau mendengarkan, terbuka terhadap ide-ide baru, dan bisa membangun suasana kerja yang kolaboratif, bukan kompetitif secara berlebihan. Mereka ingin bekerja di tempat di mana kreativitas dihargai, keberagaman diterima, dan setiap orang merasa aman untuk jadi dirinya sendiri. Kepemimpinan yang berlandaskan empati dan komunikasi bukan hanya membuat karyawan muda bertahan lebih lama, tapi juga menumbuhkan budaya kerja yang lebih hangat, positif, dan berkelanjutan.
Tentu saja, keputusan untuk meninggalkan pekerjaan bukan tanpa konsekuensi. Banyak dari mereka yang harus menghadapi ketidakpastian , mulai dari kondisi finansial yang menurun, hingga rasa cemas soal masa depan karier. Tapi bagi Gen Z, risiko itu dianggap sepadan dengan kesempatan untuk hidup lebih tenang dan berarti. Mereka sadar bahwa kestabilan bukan hanya soal gaji tetap, tapi juga tentang kedamaian batin. Dengan bantuan teknologi dan peluang kerja yang kini jauh lebih beragam, mereka bisa menciptakan jalur karirnya sendiri, entah lewat freelance, bisnis kecil, influencer, atau pekerjaan jarak jauh, semua dilakukan dengan satu tujuan yaitu hidup yang lebih waras dan kebahagiaan pribadi.
Keberanian Gen Z untuk menomorsatukan kesehatan mental sebenarnya membawa pesan besar bagi dunia kerja. Mereka sedang mengingatkan kita semua bahwa produktivitas sejati lahir dari kesejahteraan batin, bukan dari tekanan yang terus dipaksakan. Dunia kerja masa depan tak bisa lagi hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga harus menempatkan kemanusiaan di pusatnya. Generasi ini mengajarkan bahwa bertahan bukan selalu tanda kekuatan, dan pergi bukan selalu tanda kegagalan. Kadang, keputusan untuk pergi justru adalah bentuk keberanian paling jujur.
Pada akhirnya, keputusan Gen Z untuk memilih keluar bukan sekadar bentuk penolakan, tapi juga sebuah perjuangan, perjuangan untuk hidup dengan lebih seimbang, sehat, dan berarti. Mereka berani berkata “tidak” pada sistem kerja yang melelahkan jiwa, dan dengan itu, mereka membuka jalan bagi cara pandang baru tentang arti bekerja. Dunia kerja yang ideal seharusnya bukan tempat yang menguras tenaga dan perasaan, melainkan ruang yang menumbuhkan kreativitas, rasa aman, dan kebahagiaan bersama. Jika para pemimpin mau mendengarkan dan belajar dari semangat ini, mungkin dunia kerja kedepan akan menjadi lebih manusiawi, tempat di mana bekerja bukan sekadar bertahan hidup, tapi juga cara untuk merayakan kehidupan itu sendiri.
Mungkin ini saatnya kita bertanya pada diri sendiri , apakah kita bekerja untuk hidup, atau hidup hanya untuk bekerja? Pada akhirnya, bukankah tujuan kita semua sama, untuk bisa bekerja tanpa kehilangan diri sendiri?
Artikel ini telah tayang di
Mediamassa.co.id

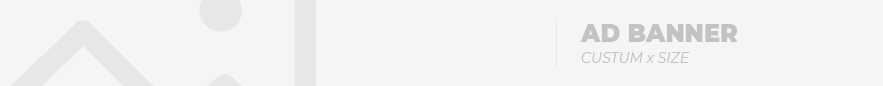
Social Header